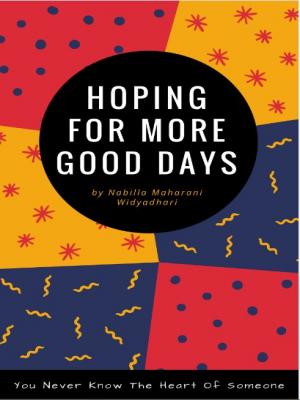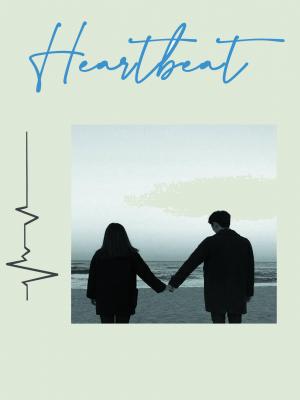Perasaan yang Terpendam
‘Sehabis melihat daftar pengumuman penerimaan siswa, aku melihatmu sedang menolong nenek yang terjatuh di depan sekolah. Kamu segera menuntunnya berjalan dan membantunya menyeberang sampai depan gedung DPRD. Nenek itu tidak sadar jika beliau menjatuhkan tasnya. Aku juga menyeberang jalan dan memberikan tas itu padanya. Aku melihatmu tersenyum padaku dan bilang..,’
‘Terima kasih. Kamu orang yang sangat baik,’ ucapan Afika masih melekat jelas di dalam benakku. Kenapa semua orang terus saja memandangku seperti seseorang yang murni dan berjiwa bersih. Padahal aku merasa tidak seperti itu. Bahkan seorang gadis yang aku sukai juga mengatakan hal yang sama padaku.
Dibandingkan aku, Miwon masih jauh lebih baik dari aku. Seberapa bencinya dulu aku kepada ayah, akan tetapi Miwon tetap menyayangiku. Dia tidak berbalik membenciku. Salah satu alasan itu juga yang pada akhirnya membuatku luluh untuk menerima ayah kembali ke dalam kehidupanku.
“Ed, kamu masih disini? Katanya pamit pulang? Ayah kira kamu sudah pulang tadi,” keberadaan ayah di samping kursi sofa cukup mengagetkanku. Tadinya aku bermaksud menjenguk ayah yang sedang sakit demam di rumah sebentar. Setelah itu hendak kembali ke Surabaya karena sebentar lagi jam kerja.
“Eh, ayah nggak perlu keluar kamar. Lebih baik ayah beristirahat saja di kamar.”
“Tidak apa-apa. Ayah ingin menghirup udara segar dulu. Di dalam kamar udaranya pengap,” ayah ikut duduk di sebelahku. “Kenapa belum pulang?”
“Tadi adek kirim chat. Katanya Miwon kangen sama aku. Dia ingin ketemuan sama aku sebentar katanya.”
Ayah tersenyum sembari menggeleng-gelengkan kepalanya.
“Dasar, anak itu. Sekarang Sukanya pulang-pergi naik motor. Mentang-mentang sudah punya pacar. Jam pulang pun suka terlambat.”
“Hahaha.. Mang Budi nganggur dong, yah?”
“Ya nggak dong! Sekarang mang Budi totalitas bisa antar-jemput ayah di kantor. Ayah nggak tega dong kalau pecat dia. Sudah berapa tahun mang Budi ikut papa. Memang cari sopir yang bisa dipercaya sekarang susah. Makanya satu hal yang harus kamu tahu tentang pekerjaan yaitu trust. Kepercayaan.”
Aku menganggukkan kepala mengerti. Tak lama terdengar suara motor dari depan halaman rumah. Rupanya Miwon sudah pulang. Aku dan ayah menunggu kehadirannya di ruang tamu. Namun aku terkejut ketika melihat Miwon tidak masuk ruangan sendirian. Ia masuk ke rumah Bersama dengan Afika. Ya, Afika, seorang gadis yang belum punah dari dasar hatiku.
“Asalamualaikum, ayah! Waa.. kakak beneran nunggu aku!!! Senangnya!” Miwon melonjak senang. Ia langsung merangkulku dengan erat.
“Hush! Sikapnya kok masih kayak anak-anak! Nggak malu sama pacar!” seru ayah gemas. Miwon tertawa terbahak-bahak.
“Tidak apa-apa, om. Saya sudah terbiasa,” ucap Afika kalem. Ayah mempersilakan mereka duduk di kursi sofa. Kami berempat bercakap-cakap sebentar. Aku mencoba untuk tersenyum saat melihat Miwon dan Afika melempar canda. Keduanya tampak akur dan sangat dekat. Hampir saja aku tidak mampu menutupi luka yang masih menganga ini. Tak lama aku pun pamit untuk kembali ke Surabaya. Ayah dan Afika mengantarku sampai di depan halaman rumah.
“Miwon masih di kamar mandi?”
“Iya. Katanya perutnya sakit sekali. Kayaknya gara-gara tadi makan bakso kebanyakan saos sambal,” kata Afika sambil tertawa kecil.
“Anak itu!” ayah bersungut-sungut lagi mendengar kisah kecerobohan anaknya. Aku pun ikutan tertawa. Tiba-tiba saja ringtone handphone Afika berdering. Ia segera mengangkatnya.
“Apa? Timmy? Kok bisa?! Ya, nanti aku akan kesana! Makasih ya sudah dikabarin,” setelah memasukkan handphone ke dalam saku, wajahnya tampak gelisah.
“Ada apa, Fik?” tanyaku. Afika mengigit bibirnya dengan wajah cemas.
“Aku tadi dikabarin Hami kalau Timmy kecelakaan. Sekarang masuk rumah sakit.”
“Lho, kok bisa? Ya ampun, Timmy..,” aku masih melihat kegelisahan dari wajah Afika. Tampaknya ia ingin segera menjenguk sahabatnya, tetapi Miwon sableng itu masih di kamar mandi. Apakah tidak apa-apa kalau aku berniat untuk mengantarnya? “Ayo, aku antar kesana.”
“Tid.. tidak usah, Ed. Makasih. Aku nunggu Miwon ajah dulu.”
“Nunggu dia sampai pantatnya meletus juga bakalan lama. Mendingan kamu bareng aku ajah. Kebetulan jam kerjaku masih lama.”
“Tap.. tapi..,” Afika masih menatapku ragu. Aku langsung memandang ayah, meminta bantuannya. Ayah menepuk bahu Afika.
“Iya, tidak apa-apa, Fik. Nanti om yang akan menyampaikan kepada Miwon kalau kamu menjenguk temanmu yang baru saja kecelakaan. Nanti om suruh dia menyusul.”
“Iy.. iya, om. Terima kasih. Saya pamit dulu, om,” Afika menyalami ayah dan mengambil helm-nya di motor Miwon. Seketika jantungku berdebar ketika Afika duduk di atas motor. Saat ini dia duduk di belakangku. Sudah lama kami tidak berboncengan Bersama lagi. Terakhir aku mengantarnya di danau Ngipik, tempat dimana aku merelakannya pergi menemui Miwon.
“Makasih ya, Ed. Kamu sudah mengantarku,” kata Afika di tengah perjalanan. Aku tersenyum senang mendengarnya berbicara denganku lagi dengan santai. “Kamu baik banget.”
‘DEG!’ Kalimat Afika barusan seolah-olah memantraiku. Tanpa sadar kemarahanku bergejolak. Ku naikkan kecepatan motorku tanpa mengerem sedikitpun. Teriakan Afika mengagetkanku. Aku segera mengurangi kecepatan motorku. Terdengar suara isak tangis Afika.
“Fik, kamu nggak apa-apa?” kuberhentikan motor di pinggir jalan. Aku langsung turun dari motor. Afika juga turun dari motor sambIl tidak berhenti menangis. “Kamu nangis?”
“Ma.. maaf, Ed. Aku takut kalau kamu ngebut kayak tadi. Aku takut jatuh,” Afika menghapus sisa-sisa air matanya yang sedari tadi mengalir. Aku langsung merutuki diriku sendiri. Kenapa aku malah melampiaskan kemarahanku padanya. Itu bukan salah Afika!
“Maafkan aku ya, Fik. Aku tadi agak sedikit marah.”
“Ed Marah? Kenapa..?” pertanyaan Afika membuatku merutuki diriku kembali. Kenapa aku bisa sejujur ini padanya? Aku tidak ingin menyakiti hatinya.
“Eh, nggak. Ayo kita lanjutkan perjalanan.”
Kuputuskan untuk meredam emosiku sebisa mungkin. Sepanjang perjalanan kami tidak berbicara sepatah kata pun. Sesampainya di rumah sakit, kami memasuki ruang UGD dan menemukan Hami yang sedang menjaga Timmy disana. Keadaan Timmy cukup miris. Banyak luka dari tangan dan kakinya. Salah satu pergelangan tangannya mengenakan gips.
“Duh, Afika. Cakiiitttt,” kemanjaan Timmy mengingatkanku dengan Miwon yang tidak berbeda jauh dengan gadis mungil itu. Afika mengelus kepala Timmy dengan lembut.
“Gimana bisa kamu seperti ini sih?!” seru Afika. Kulihat wajah cemasnya kesekian kali. Ia tidak berubah. Masih saja memikirkan dan mengkhawatirkan orang-orang disekitarnya. Kenapa gadis selembut itu tidak bisa berada di sisiku? Seandainya waktu itu aku tidak melepaskannya, apakah ia masih berada disisiku sampai hari ini?
“Tadi aku pulang boncengan motor sama Hami. Terus saat di jalan ada jambret. Diam au ngambil tas laptopku. Aku pertahanin dong. Nggak tahunya kita jatuh berdua di jalan,” cerita Timmy kemudian.
“Aku sih nggak apa-apa. Tapi Timmy terseret di jalanan. Laptopnya juga diambil sama tuh jambret. Gara-gara itu, tangannya terkilir dan harus pakai gips,” sambung Hami.
“Huhuhu.. laptop kesayangankuw. Banyak fanfiction yang aku buat lagi disitu,” Timmy memeluk pinggang Afika dengan erat. Afika mencoba menenangkannya. Aku tidak menyangka gadis mungil itu juga gemar menulis toh! Aku kira dia hanya tahu soal dandan. “Heh! Apa ketawa-ketawa?!”
Aku agak terkejut karena Timmy menyadari kehadiranku. Aku yang semula berdiri di belakang Afika langsung mendekati Timmy sembari tersenyum.
“Kamu tertarik nggak ikut mading?” Timmy berdiri dihadapanku sambIl berkacak pinggang dengan tangan kirinya yang tidak di gips.
“Nyindir ya? Mentang-mentang aku K-Popers. Suka nulis fanfiction gitu?”
“Loh, aku serius loh.”
“Huh. Sori ya. Bayaranku mahal tahu. Dibandingkan dengan karya-karya di mading, karyaku itu karya dari tangan dewa! Karyaku itu..,” Afika segera membungkam mulut Timmy yang terus saja nyerocos. Aku tidak mampu menahan tawa lagi. Kelakuan gadis mungil bak boneka itu selalu saja membuatku ingin tertawa.
“Tuh kan! Waktu di wahana pesawat helikopter juga kamu nggak berhenti ketawa. Apa aku selucu itu?” tanyanya dengan wajah merengut. Aku hampir tertawa lagi melihat ekspresinya. Namun kali ini aku tahan. Ku tepuk kepalanya dengan lembut.
“Kamu memang selucu itu,” kini wajah Timmy malah memerah. Ia menjadi agak salah tingkah. Timmy berhenti melihatku dan bertanya pada Afika kenapa Miwon tidak datang menjenguknya. Afika mengatakan bahwa Miwon masih sakit perut di rumah ayah. Kutepuk bahu Afika. “Fik, aku pamit dulu ya. Sudah jam nya nih.”
“Oh, iya, Ed. Makasih ya,” jawabnya. Timmy berbisik di telinga Afika. Lalu berbaring di atas kasur lagi. “Uum, Ed. Timmy katanya mau bicara sama kamu sebentar. Aku dan Hami keluar dulu ya.”
Afika menarik Hami keluar ruangan. Lantas aku duduk di kursi yang berada di dekat Kasur Timmy. Aku menunggu sampai ia berbicara duluan. Tapi ia masih terdiam sembari menatap langit-langit. Aku pun memutuskan untuk membuka pembicaraan duluan.
“Kenapa masih di UGD?”
“Ya jelaslah masih disini. Aku masih menunggu obat dari perawat untuk dibawa pulang nanti.”
“Lalu.. Timmy mau ngomong soal apa?”
“Ekhem,” dia berdehem sebentar sebelum melihatku lagi.
“Ed masih suka Afika ya?”
“Hah?”
“Kelihatan loh dari wajahnya,” ucapnya dengan tatapan nyinyir.
“Kelihatan darimananya? Memangnya ada tulisan di wajahku gitu?” sungutku hampir kesal dibuatnya. Aku mencoba untuk tidak terlihat seperti itu.
“Memang! Tuh ada tulisannya di jidat ‘mantan yang susah move on'.”
Aku pun terperangah mendengarnya.
“Memangnya terlihat seperti itu ya?” Timmy mengangguk dengan mantap. Aku pun merasa malu. Ingin sekali kusembunyikan wajahku di tempat tertutup sehingga Timmy tidak dapat membaca jelas wajahku saat ini.
“Lho kok jadi sedih? Aku Cuma bercanda loh, Ed.”
“Bercandamu keterlaluan tahu!!!” ku cubit kedua pipinya yang tembam itu. Dasar licik! Bisa-bisanya mempermainkan perasaanku yang masih terluka ini. Timmy mengaduh kesakitan. Aku pun teringat kemarahanku pada Afika di jalan tadi. “Hey, Tim. Sebenarnya di motor tadi aku ngebut loh saat boncengan sama Afika.”
“HAH! SERIUS?! Baru tahu seorang Edelweis yang baik hati dan tidak sombong bisa ngebut juga ternyata!”
“JANGAN SEBUT AKU BAIK..!!!” bentakku kemudian. Aku terdiam sejenak. Lagi-lagi aku tidak mampu mengontrol emosiku. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. “Maaf, Tim.”
“Afika juga selalu bicara begitu kan?” tanyanya. Aku kembali menatap Timmy yang menatapku dengan senyuman tipis. “Edelweis adalah orang yang baik dan dia selalu hebat dimataku. Kata-kata seperti itu yang selalu membebanimu, iya kan?”
“Aku tidak sebaik yang kalian kira. Aku tidak ingin menjadi orang baik di mata Afika. Karena kenyataannya aku masih merasa tersakiti dengan keputusannya saat itu. Aku merasa dipermainkan oleh dua orang itu.”
“Dua orang itu?”
“Afika dan Miwon. Keberadaan mereka yang mesra itu selalu membuatku risih. Kenapa bukan aku yang berada di sisi Afika? Ingin sekali aku memaki Afika. Ingin sekali aku menghantam wajah Miwon.”
“Kalau begitu maki saja Afika! Pukul saja Miwon!”
“Apa?” tanyaku tidak mengerti. Timmy kan teman terdekat Afika dan Miwon. Kenapa dia merelakan aku melakukan hal itu kepada mereka berdua?
“Tidak baik loh memendam perasaan benci lama-lama. Karena perasaan itu akan semakin lama membesar dan suatu saat akan meledak menghantammu. Pada kenyataannya dirimu sendirilah yang tidak mampu berdiri menopang rasa benci itu,” ucapnya panjang lebar. “Jika Afika berbalik memakimu dan Miwon membalas pukulanmu, itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah Ed merasa lega dan puas karena telah mengungkapkan semuanya secara gamblang. Tidak menutup-nutupinya seperti sekarang. Sepanjang kamu mengutarakan alasanmu kenapa kamu memaki Afika dan kenapa kamu memukul Miwon, aku rasa mereka akan mengerti.”
Aku mencoba mencerna kata-kata Timmy. Aku tidak menyangka gadis mungil yang biasanya hanya bercanda dan doyan dandan itu ternyata mampu mengatakan semua hal itu padaku.
“Baiklah. Aku akan mencoba memahami kata-katamu itu. Kalau aku sudah yakin, aku akan melakukan semua itu kepada mereka berdua. Thanks ya, Tim.”
“Okey-dokey, mas bro!” serunya sambil melemparkan kerlingan mata padaku. Aku tertawa lagi melihat kelakuannya yang absurd itu. Timmy cemberut lagi karena aku tidak berhenti tertawa.
“Kalau begitu aku pamit dulu ya. Sudah waktunya jam kerja nih. Get well soon, okay?” aku menepuk-nepuk kembali kepalanya dengan lembut. Entah kenapa Bersama dengan Timmy membuat bad mood-ku hilang begitu saja. Keberadaannya itu moodboster banget buatku. Hampir saja aku berbalik meninggalkannya. Timmy memanggilku lagi. Aku pun berbalik dihadapannya lagi. “Apa yang ingin kamu katakan lagi, Timmy Winnie bittie?”
Timmy menunjuk tepat di dadaku.
“Ed.. kalau Afika sudah tidak ada di dalam sana, aku boleh mencoba singgah kan?”
***
 **NANTIKAN BONUS TERAKHIR DARI KISAH ADOLESCERE LOVE, YAY! SAMPAI BERTEMU LAGI!**
**NANTIKAN BONUS TERAKHIR DARI KISAH ADOLESCERE LOVE, YAY! SAMPAI BERTEMU LAGI!**


 Aijinchan
Aijinchan