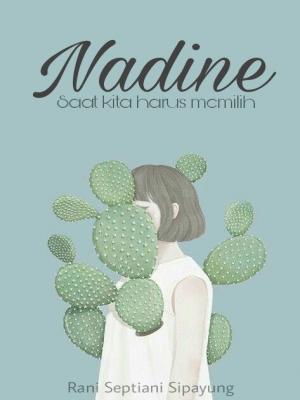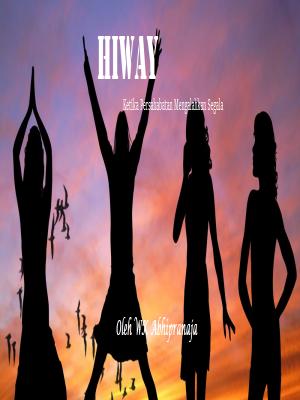Arungi Muara - Keping Lima
“Loteng Berlubang”
Risa mengangkat teleponnya yang beberapa detik lalu bergetar. Ia memang tak menyukai suara dering ponsel yang memekkakan telinga. Risa hampir selalu mengatur telepon genggamnya dalam mode getar atau bahkan diam. Risa tak suka jika aktivitasnya terinterupsi panggilan masuk. Dan sebab itu, ia kini menyesal telah membuat ponselnya itu bergetar. Harusnya akhir dari percakapan itu adalah Risa mengirim pesan: “Sorry, barusan hape saya silent. Bisa sms saja?” Namun kali ini Risa tak bisa memakai alasan itu. Risa bukanlah seorang yang mudah berbohong. Sekalipun orang yang hendak ia bohongi tak tahu jika ia sedang berbohong.
“Hallo?” jawab Risa, enggan. Tangannya sibuk mengetik apply CV-nya untuk melamar ke beberapa perusahaan kota.
“Risa, we need to talk,” sahut seseorang dari seberang.
Risa memutar bola mata. “Come on, Sister. You're talking now.”
“Dad called me last night,” potong wanita di telepon. Risa sontak membeku. Jari-jarinya terpaku di atas keyboard laptop.
“Apa? Kakak bilang apa barusan?” Risa memastikan. Walau sejatinya Risa tak perlu meragukan pendengarannya sendiri.
Wanita itu mendesah resah. “I know you heard me, Sist. I know you did.”
“Terus kenapa Kakak bilang ke aku masalah ini?” tanya Risa. Intonasi suaranya mendadak dingin. Seperti robot.
“Ayolah, Risa. He's your dad. I think it's time for us to give him a second cha—”
“I don't have dad since I was two! You knew that, Kayla!” pekik Risa.
“Tapi Ayah bilang—”
“I don't give a damn about what did he say to you!” jerit Risa. “Just handle him, please.” Risa membenamkan punggungnya ke sandaran kursi. Semakin dalam. Tubuhnya seolah kehilangan kekuatan, gemetar tak karuan.
“Sampai kapan kamu anggap dia enggak pernah ada, Ris?” lirih Kayla.
“Kakak bilang aku enggak pernah anggap dia ada?” tanya Risa, sarkastik. “Kakak pengacara kondang di Amerika. Lulusan S1 dan S2 Harvard dengan gelar cumlaude, dan kakak tahu, omongan Kakak barusan… it seems like… you have mocked your own title.”
Kayla diam. Jauh di sana pikirannya berkecamuk. Ia bisa membayangkan wajah datar sarat luka yang Risa pertunjukan di depan laptop yang memang ada di hadapannya.
“Dia yang anggap kita enggak ada. Seperti kita enggak pernah lahir. Terus sekarang Kakak bilang gini ke aku?” tutur Risa, “apa gunanya Kakak sekolah tinggi-tinggi tapi enggak bisa mikir perasaan adik sendiri?”
Kayla diam. Air mata di pelupuknya.
Risa mengatur napas. Udara seolah tersendat di kerongkongannya. Membuat paru-parunya tak terisi udara, sesak setengah mati rasanya. “Kakak… bisa atur, kan? You… you exactly can handle this situation, can't you?”
Kayla hanya diam. Bicara tentang pasal-pasal politik dan menohok banyak orang dengan teorinya memang mudah. Tetapi lidahnya tak sanggup bergerak barang sejengkal pun saat sudah hadapkan dengan adiknya sendiri.
“Aku cuma minta satu hal,” ujar Risa, sebelum panggilan itu berakhir, “tolong bilang kalau Kakak udah enggak pernah ketemu sama aku sejak bertahun lalu. Kalau Kakak telanjur bilang, bohong.”
“Berbohong tentang keberadaan kerabat terdekat bisa diberi sanksi—”
“Kira-kira apa hukuman untuk seorang bapak yang sudah meninggalkan anaknya bahkan sejak berumur dua tahun tanpa memberi anak-anaknya nafkah sama sekali?” sela Risa, “apa ada pasal yang mengatur tentang itu, Kak?”
Lagi-lagi, Kayla bungkam.
Risa melanjutkan, “Jangan pernah beritahu dia tentang keberadaan aku, Kak. Kalau Kakak lakuin itu, aku enggak segan-segan untuk kabur. Dan ini bukan perintah, ini ancaman. Karena kalau Kakak mencoba untuk mencari, aku enggak yakin Kakak bakal nemuin aku setelah itu.”
*
Rain mengetuk pintu di hadapannya dengan seulas senyum lesu. Rain tak tahu mau lari ke mana lagi. Dia memang sudah mencoba untuk menginap di beberapa kos milik temannya. Tetapi perantauannya mencari tempat tinggal sementara itu berakhir dengan Rain yang harus membayar sebagian uang kos temannya karena ternyata teman Rain itu pun juga belum membayar kos. Sial memang.
Dan kemudian, pintu di depan Rain terbuka. Disambutlah ia oleh Thessa, si bule Brazil seksi yang selalu enak untuk dilihat. Mata Rain langsung mengerjap bak disetrum aliran listrik satu komplek. Thessa hanya memakai T-shirt ketat dan hot pant super mini. Bisa ditebak, Rain menunjukkan reaksi biologis akan pemandangan tersebut. Lagipula, lelaki mana yang tidak suka wanita seksi?
“Hey, Rain!” sapa Thessa girang.
“Hey, Thes,” sahut Rain.
“Just come in!” Thessa mempersilakan Rain masuk.
Rain menghenyakkan tubuh di atas sofa ruang tamu. “Risa pasti udah kasih tahu kamu tentang tujuanku ke sini, kan?”
Thessa mendaratkan pantat di samping Rain. “Yeah, she did.”
Rain mengusap wajah. “Oke, Thes. Aku enggak bermaksud kurang ajar main langsung nginep di sini. Tapi… aku bener-bener butuh, Thes. Aku enggak tahu lagi mau tinggal di mana. Dan aku janji, aku janji aku bakal langsung keluar dari sini begitu dapat kerja, bayar fee yang emang sudah seharusnya aku bayar ke kamu, dan—”
Thessa terbahak. “Wow, wow. Slowly, Buddy. Kamu ngomong nyaris tanpa jeda, Rain.”
Rain diam.
“With pleasure I accept you here,” ujar Thessa, kalem. Rain terpana. Thessa menepuk pundak Rain, “saya ambilkan minum dulu.”
*
Rupanya apa yang Risa pernah bilang ke Rain itu ada benarnya. Risa benar mengenai loteng kosong yang ada di rumah ini. Rain betul-betul akan menjadi penghuni loteng tersebut malam ini juga. Berhubung barang-barang Rain di kos tak terlalu banyak, membuat ia tak butuh waktu lama untuk memindahkannya kemari.
Loteng itu hanyalah ruangan 3x4 meter yang sempit dan pengap. Di kirinya langsung tersambung tangga ke lantai bawah. Dan di sudut ruang terdapat pintu, yang jika dibuka akan menyajikan Rain pemandangan indah dari pakaian dalam milik Thessa dan Risa yang tengah bertengger apik di seutas tali yang melintang. Itu adalah tempat menjemur pakaian.
Di loteng itu tak ada pintu. Tak ada privasi. Namun Rain patut bersuka hati. Thessa yang baik memberi ini semua gratis.
Rain tengah memindah pakaiannya ke dalam sebuah lemari plastik bersusun yang tadi Thessa beri. Bule itu memang terlalu baik. Terlalu seksi juga, pikir Rain. Kemudian terdengar langkah kaki dari balik punggung. Rain menoleh, lalu menjumpai satu sosok yang tak asing. Rain tersenyum.
“Hey, Ris,” sapanya. “Ngapain di sini? Inikan udah malem.”
Dengan baju tidurnya Risa mendekati Rain. Memerhatikan pekerjaan Rain sejenak, lalu mengidikkan bahu. “Kata Thessa, saya disuruh kenalan sama penghuni baru,” jawab Risa seadanya.
Rain mengangkat alis. “Oh. Kenalin, aku Rain Sanjaya.”
Risa menjawab, “Saya Risa Naveena Veronica. Salam kenal, Rain.”
Kemudian mereka terbahak hambar. Risa mengamati sekitar. Loteng itu telah disulap oleh Rain menjadi kamar tidur sederhana yang setidaknya layak huni. Ada kipas angin di atas lemari plastik. Keranjang cucian kotor di sampingnya, sebuah kasur lipat tipis di dekat kaki Risa. Tidak buruk, batin Risa.
“Saya pikir di sini gerah. Ternyata enggak, ya?” tanya Risa.
Rain menjawab, “Mungkin karena itu.” Rain menunjuk dengan dagu.
Pandangan Risa terkunci pada objek yang ditunjuk oleh Rain. Dan rupanya, ada sebuah lubang yang lumayan besar di sudut loteng ini. Jelas saja tidak panas, angin malam pasti bisa masuk lewat sana.
“Kok ada lubang segede itu?” tanya Risa heran.
“Mana aku tahu, Ris. Tahu-tahu aku dateng udah ada itu lubang,” jawab Rain.
“Saya suruh Thessa panggil tukang, deh, kayaknya.” Risa bersiap membalikkan tubuh.
Namun Rain memekik, “Eh, Ris! Enggak usah!”
Risa melipat dahi. “Kenapa?”
“Ini udah malem. Jangan gangguin Thessa. Dia pasti udah tidur. Kapan-kapan aja manggilnya. Kan masih bisa,” ujar Rain.
Risa mengalah. Namun tiba-tiba Rain terkekeh. Risa menyernyit. “Kenapa, Mas?”
“Kamu perhatian sama aku, ya, Ris?” tanya Rain. “Kamu takut aku masuk angin, kan? Makasih, lho, Ris. Aku terhura.”
Kedua mata Risa membeliak lebar. Mulutnya ternganga. “Mas Rain itu… punya penyakit namanya geer kronis, ya?” Risa menggeleng tak percaya.
Rain tergelak. “Aku bercanda, Ris. Astaga.”
“Saya cuma khawatir, kalo hujan pasti airnya ikutan masuk. Kalo banjir sampai ke bawah gimana?! Kalo masuk ke kamar saya gimana?!” ujar Risa bersungut-sungut.
Rain mendengus geli. Dimasukkan olehnya pakaian terakhir ke dalam lemari. Ia duduk di atas kasur tipisnya, kemudian menatap Risa. “Don't worry too much, Ris,” katanyanya. “Kamu itu tipe orang yang cenderung berprespektif sama masa depan, ya?”
“Barusan itu cuma kemungkinan yang bisa aja terjadi,” sahut Risa.
“Aku bukan tipe orang yang mau repot-repot mikirin kemungkinan yang bakalan terjadi di masa depan.” Rain mengangkat bahu, “I am type of person who living in the moment.”
“Kalau prinsip Mas Rain kayak gitu, Mas Rain enggak memikirkan risiko dari tindakan yang Mas Rain lakukan, dong?” tanya Risa, sinis.
Rain menggeleng. “Kalau begitu, adanya aku yang stres sendiri,” jawabnya. “Aku cuma pingin kamu enggak terlalu gampang repot.”
Risa diam. Hidup tanpa direpotkan oleh sesuatu itu terdengar mustahil bagi Risa.
“Lagipula… lubang itu masih ada manfaatnya, kok,” kata Rain sambil memandangi atap loteng itu, “aku bisa hemat listrik. Tiap malam, aku enggak usah nyalain kipas angin.”
Risa langsung membalikkan badan. Menuruni tangga dengan langkah besar-besar. Mulutnya berseru, “Terserah!”
*
“We must be able to see a beautiful thing even in the worst condition. So that we can be thankful.” -NLH


 litaanaya
litaanaya